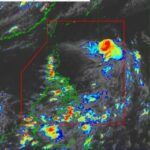TOKOROZAWA, Prefektur Saitama – Yatim perang Jepang yang tertinggal di Tiongkok di tengah kekacauan di akhir Perang Dunia II dan direpatriasi ke Jepang beberapa dekade kemudian, kini memasuki usia senja.
Banyak yang kesulitan beradaptasi dengan panti jompo konvensional karena hambatan bahasa. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, Mariko Kamijo (47), putri tertua dari seorang yatim yang direpatriasi, membuka fasilitas perawatan yang memberikan dukungan dalam bahasa Mandarin.
Suatu hari di Isshoen, fasilitas perawatan di Tokorozawa, Prefektur Saitama, Jepang timur, 10 klien mengikuti latihan ringan dan kegiatan rekreasi, sesekali berseru, “Yi, er, san, si,” yang berarti satu, dua, tiga, empat dalam bahasa Mandarin. Sebagian besar percakapan di ruangan itu juga menggunakan bahasa Mandarin.
Lebih dari separuh dari sekitar 30 orang yang menggunakan fasilitas ini, termasuk pasangan mereka, adalah orang Jepang yang pergi ke Tiongkok saat masih anak-anak selama perang, ketika sebagian wilayah negara itu berada di bawah kendali Jepang, dan kemudian tertinggal di sana. Beberapa sedikit atau sama sekali tidak bisa berbahasa Jepang. “Saya memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah orang tua saya sendiri,” kata Kamijo, yang menyapa mereka dalam bahasa Mandarin.
Dia terinspirasi untuk memulai bisnis perawatan lansia setelah mengetahui pengalaman ayahnya, Mitsuhiko (87), yang tertinggal di Tiongkok pada usia 7 tahun.
Istilah “yatim perang Jepang yang tertinggal di Tiongkok” merujuk pada anak-anak, kebanyakan di bawah usia 13 tahun, yang terpisah dari keluarga mereka di bekas Manchuria dan bagian lain Tiongkok, lalu diambil oleh keluarga Tiongkok setelah Uni Soviet memasuki perang melawan Jepang pada Agustus 1945, yang melanggar pakta netralitas bilateral mereka.
Mitsuhiko lahir pada 1938 di Prefektur Nagano, Jepang tengah, dan menghabiskan sebagian masa kecilnya di Beijing dan daerah lain di Tiongkok. Setelah perang, saat tinggal bersama kerabat di wilayah yang saat itu disebut Manchuria di timur laut Tiongkok, dia dibujuk oleh seseorang yang menjanjikan pertemuan dengan orang tuanya dan dibawa ke rumah seorang pria Tiongkok tunanetra yang kemudian mengadopsinya. Mitsuhiko ingat bahwa dia “menjadi matanya,” bercerita melalui putrinya sebagai penerjemah.
Tidak bisa bersekolah, dia mulai bekerja sejak muda, magang sebagai tukang cukur pada usia 13 tahun. Dengan berlinang air mata, dia mengatakan bahwa dia selalu ingin kembali ke Jepang.
Upaya melacak kerabat Jepang dari para yatim yang tertinggal mulai mengemuka pada 1981, ketika survei dan kunjungan ke Jepang yang didukung pemerintah dimulai.
Sekitar 1983, Mitsuhiko mulai mencari keluarganya dengan menghubungi Kedutaan Besar Jepang di Beijing. Dia telah lupa bahasa Jepang dan tidak bisa mengingat nama lengkap atau tanggal lahirnya di Jepang. Meski begitu, serpihan ingatan—nama keluarga yang mengandung “Kami,” bermain masa kecil di Danau Suwa di Nagano, dan seorang adik perempuan dengan luka bakar di salah satu lengannya—membawa terobosan. Pada musim panas 1985, kakak laki-lakinya, yang telah mencarinya selama bertahun-tahun, akhirnya melacaknya di Jepang.
Selama kunjungan ke Jepang tahun berikutnya, Mitsuhiko bertemu kembali dengan orang tua dan kerabat lainnya. Dia mengatakan tidak bisa mengungkapkan kebahagiaannya dengan kata-kata. Pada Oktober 1995, dia pindah ke Jepang bersama tiga anggota keluarga. Saat itu usianya 57 tahun, dan putri tertuanya berusia 17 tahun.
Sekitar dua bulan kemudian, Mitsuhiko menderita pendarahan otak yang membuatnya mengalami disabilitas fisik. Sekitar usia 70 tahun, dia mulai membutuhkan perawatan lansia dan mulai menggunakan layanan penitipan harian.
Suatu hari, Mitsuhiko bercerita kepada keluarganya tentang sebuah insiden di fasilitas perawatan tempat dia dirawat. Saat waktu mandi, dia dibiarkan telanjang. Menggigil kedinginan, dia tidak bisa meminta tolong karena tidak mengerti bahasa Jepang.
Setelah mendengar pengakuan Mitsuhiko yang penuh air mata bahwa perang telah “mengguncang”